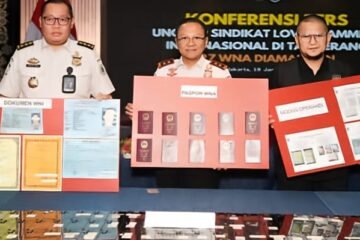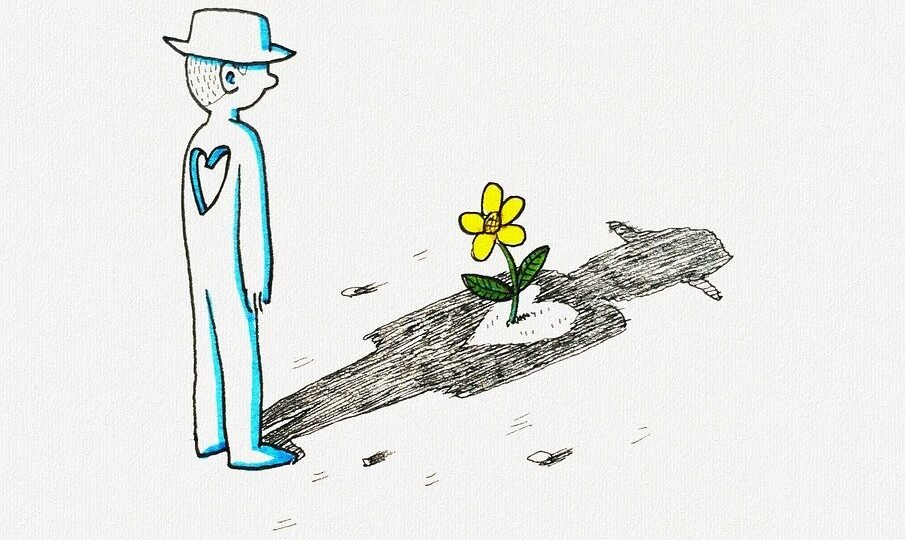
Foto: Pixabay
Marhaen yang Dipenjarakan, Roh yang Merdeka
- Oleh Delpiero Hegelian
Hegel menggambarkan sejarah sebagai panggung di mana roh dunia menampakkan dirinya. Ia bergerak melalui dialektika, mencapai tesis, antitesis, dan sintesis. Namun, panggung sejarah Indonesia saat ini tampaknya penuh dengan tragedi. Seorang Marhaen, simbol rakyat kecil yang berani bersuara, justru ditangkap atas nama hukum.
Pertanyaannya adalah, “Siapakah yang sebenarnya sedang menjadi subjek dalam dialektika sejarah ini?” Apakah negara yang menahan tubuh Marhaen, atau Marhaen yang dengan suaranya mencegah negara menjadi republik tanpa suara?
Marhaenisme, sebagaimana pernah diajarkan Bung Karno, adalah filsafat perjuangan rakyat kecil: petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota. Marhaenisme lahir sebagai semangat pembebasan, menuntut agar rakyat tidak sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi subjek dari sejarah. Dalam perspektif kebijakan publik, Marhaen adalah cermin paling nyata dari “warga negara” yang semestinya dilayani negara. Namun ketika Marhaen bersuara, ia dianggap mengganggu. Suaranya dipandang bising, tidak produktif, bahkan subversif. Maka negara menghadirkan antitesis: hukum dijadikan palu untuk memukul kepala Marhaen, bukan payung untuk melindunginya.
Indonesia, melalui konstitusi menyebut negara ini adalah negara hukum (rechtsstaat). Namun dalam praktiknya, hukum sering kali tidak lebih dari instrumen kekuasaan (machtsstaat), pasal – pasal lentur, seperti karet gelang murahan digunakan untuk membungkam, bukan membebaskan.
Dalam kacamata Hegelian, ini adalah negasi terhadap kebebasan. Sebab, kebebasan bukanlah ketiadaan hukum, melainkan hukum yang rasional, yang diakui oleh kesadaran umum sebagai wujud kebebasan itu sendiri. Ketika hukum kehilangan rasionalitasnya dan hanya menjadi alat represi, ia berhenti menjadi hukum; ia hanyalah kekerasan yang menyamar sebagai keadilan.
Penangkapan Marhaen hari ini mungkin adalah antitesis dari demokrasi, tetapi dialektika sejarah menjanjikan bahwa represi bukan akhir. Justru dari represi lahir kesadaran baru bahwa demokrasi tidak bisa sekadar prosedur, tetapi harus dijaga dengan air mata dan keberanian.
Marhaen yang dipenjara hari ini sesungguhnya telah melampaui dirinya sendiri. Tubuhnya mungkin terkekang, tetapi suaranya menjelma simbol. Ia menjelma menjadi simbol perlawanan, yang kelak akan menuntut sintesis baru: tatanan politik yang lebih adil, hukum yang lebih rasional, dan negara yang lebih manusiawi.
Demokrasi kita menyusut menjadi sekadar pesta lima tahunan, sementara partisipasi kritis dianggap mengganggu. Padahal, demokrasi tidak berhenti pada prosedur, melainkan jalan menuju kebebasan yang sejati. Ironisnya, negara yang seharusnya menjadi manifestasi kebebasan justru tampil sebagai negasinya. Ia takut pada suara kecil seorang Marhaen, seolah-olah satu suara mampu mengguncang pilar kekuasaan. Mungkin inilah sarkasme sejarah: kekuasaan yang mengaku besar ternyata gemetar di hadapan rakyat kecil.
Apa yang bisa dilakukan?
Pertama, hukum harus kembali ke rasionalitasnya. Hukum yang adil adalah hukum yang melindungi kebebasan, bukan menindasnya. Reformasi regulasi diperlukan agar pasal-pasal karet tidak lagi menjadi senjata.
Kedua, negara harus belajar berdialog. Kritik bukan racun, melainkan obat pahit yang menyehatkan demokrasi. Jika negara terus menolak kritik, ia sedang menolak kemungkinan menjadi lebih baik.
Ketiga, kesadaran warga harus dipertajam. Hegel menyebut bahwa kebebasan sejati hanya terwujud ketika individu sadar akan kebebasan dirinya dalam kebersamaan. Dengan kata lain, Marhaen bukan hanya simbol, melainkan refleksi kita semua.
Sebagai penutup, penangkapan seorang Marhaen bukan sekadar peristiwa hukum. Ia adalah peristiwa filsafat, negara sedang diuji: apakah ia akan tetap terjebak dalam antitesis kekuasaan, ataukah berani melangkah menuju sintesis kebebasan. Meminjam istilah Hegel, mungkin Marhaen yang dipenjara hari ini adalah roh yang akan membebaskan kita esok hari.
Veritas Vos Liberabit
Delpiero Hegelian, kakak Delpedro Marhaen