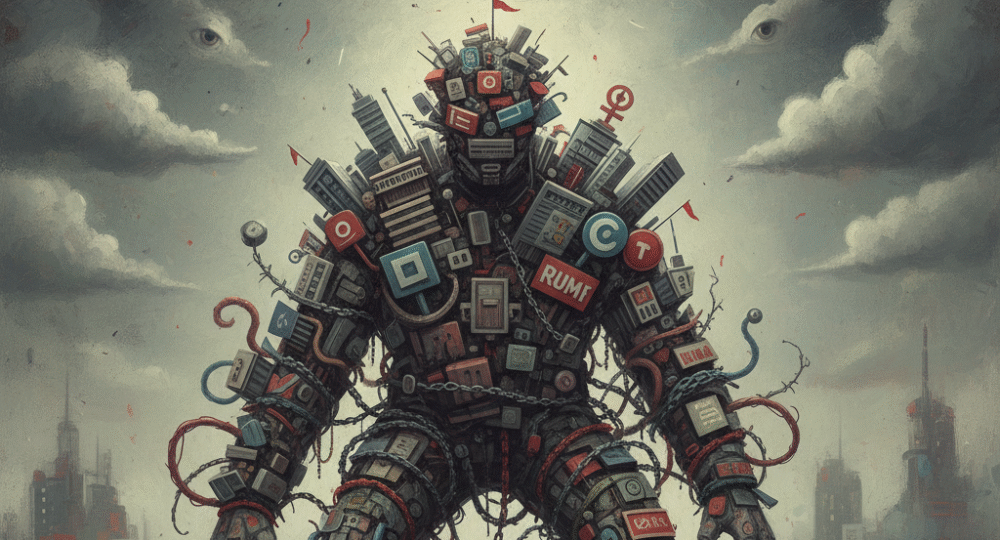
Gambar ilustrasi dihasilkan oleh AI
Catatan Kritis Penangkapan Delpedro dan Para Aktivis: Pola Berulang Pengkerdilan Ruang Sipil
- Oleh Hasnu Ibrahim
Penangkapan Delpedro Marhaen dan sejumlah aktivis muda yang memperjuangan pemenuhan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Penguatan Ruang Sipil (Strengthening Civic Space) pada akhir Agustus hingga September 2025 lalu bukan skandal penangkapan koruptor dan pejabat negara atau penangkapan jaringan konglomerasi yang meraup untung dari kebijakan publik, menggarong uang negara, serta mengeruk kekayaan alam negeri ini—melainkan simbol kontemporer dari pola sistemik berulang: ketika negara tak nyaman terhadap kritik, maka ruang sipil dikecilkan lewat mekanisme hukum atas nama “keamanan negara dan ketertiban umum”.
Secara konseptual, shrinking civic space atau penyempitan ruang kebebasan sipil merupakan pengekangan hak-hak pokok yang melandasi kebebasan masyarakat sipil yaitu hak atas kebebesan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Shrinking Civic Space pada dasarnya adalah upaya pembuat dan atau pemegang kekuasaan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam berpartisipasi demi pembangunan negara dan pemerintahan ke arah yang demokratis (Lokataru, 2020).
Padahal, partisipasi politik masyarakat sipil dalam pemerintahan sebuah rezim politik, idealnya harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya warga guna merebut dan mengklaim hak-hak mereka yang hilang, serta bertujuan mempengaruhi struktur sosial, politik, dan ekonomi di level negara yang didominasi oleh segelintir orang yang korup, nepotisme, dan kolusi, serta acap kali membangun “kartel ekonomi politik” yang menambah daftar panjang kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dan disparitas wilayah serta perbedaan akses di Indonesia.
Jika berbicara terkait hak-hak dasar warga negara, kita bisa pergi pada pengakuan kovenan dan deklarasi HAM internasional yang telah diadopsi dan diratifikasi oleh Indonesia serta dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945. Setidaknya, dalam Pasal 28 (E) UUD 1945 telah menyebut secara jelas, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Kalau dilihat secara utuh, ketiga hak utama kebebasan sipil di atas adalah derogable rights atau hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya. Namun hal tersebut tidak otomatis menjustifikasi setiap pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak tersebut. Hukum HAM Internasional telah menentukan beberapa standar, syarat, dan kondisi tertentu yang harus dipenuhi negara sebelum membatasi atau mengurangi derogable rights.
Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU 12/2005, menyebutkan, “pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum.”
Membedah Pasal ini, ada dua prinsip utama yang wajib diperhatikan negara dalam pembatasan kebebasan berekspresi yaitu prinsip legalitas dan necessity. Di bawah prinsip legalitas, ruang lingkup, interpretasi dan hukum yang akan diberlakukan dalam pembatasan kebebasan berekspresi harus ditetapkan secara jelas. Sedangkan di bawah prinsip keharusan (necessity), negara harus dapat membuktikan hubungan langsung antara kebebasan berekspresi dan ancaman yang menjadi basis pembatasan (Lokataru, 2020).
Merujuk Pasal 4 ICCPR dan General Comment No.29 Komisi Hak Asasi Manusia PBB, memandatkan, sebelum negara dapat mengambil langkah-langkah pembatasan, ada dua kondisi utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu; situasi yang dihadapi telah mencapai public emergency yang mengancam kehidupan bangsa; dan negara harus mengumumkan situasi kedaruratan tersebut.
Ada beberapa kriteria langkah-langkah yang dapat diambil negara jika merujuk pada Pasal 4 tersebut, yakni; sangat diperlukan dalam keadaan darurat tersebut; tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional; dan tidak mengandung diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.
Alih-alih memperhatikan sejumlah standar, kriteria, dan kondisi tersebut, negara dalam merespons peristiwa Agustus lalu memburu mereka yang tak bersalah—mereka dituduh melakukan perbuatan mengajak atau menghasut, provokasi, menyebar berita bohong, mengeksploitasi anak, dan bertindak anarkis dalam menciptakan kerusuhan dan penjarahan di berbagai wilayah di Indonesia.
Sialnya, bukti-bukti yang dipaparkan pihak kepolisian terlihat lemah, cocoklogi, dan upaya pengkerdilan ruang sipil secara nyata yang dialamatkan kepada masyarakat sipil yang merindukan keadilan sosial dan kesejahteraan di negeri ini.
Data dan Fakta: Mereka yang Ditangkap Polisi
Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa Agustus 2025 lalu bermula dari kecaman terhadap kebijakan dan tingkah anggota parlemen yang ugal-ugalan serta insiden tewasnya pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan. Fakta tersebut, memunculkan respons publik yang meluas sebagai akumulasi kemarahan warga.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, terdapat 1.683 orang ditahan oleh Polda Metro Jaya dalam peristiwa 25-31 Agustus 2025 (Kompas, 1 September 2025). Sementara itu, Mabes Polri mengungkap terdapat 959 orang sebagai tersangka terkait aksi 25-31 Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 664 tersangka (orang dewasa) dan 295 lainnya anak-anak di bawah umur (Portal Humas Polri, 24 September 2025).
Sementara itu, Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang dalam demonstrasi yang berlangsung selama sepekan di area Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, pada 25-31 Agustus 2025. Jumlah tersebut terdiri dari 611 orang dewasa dan 629 anak-anak (Tempo, 2 September 2025).
KontraS mencatat setidaknya 10 orang hilang pasca unjuk rasa Agustus 2025. Bahkan, sebelumnya KontraS menerima 23 laporan orang hilang dari sejumlah wilayah di Indonesia (KontraS, 1 September 2025). Kemudian, Amnesty International Indonesia mencatat berulangnya pemolisian kekerasan yang sistematis dan meluas selama demonstrasi berjalan di 14 kota dari 22 hingga 29 Agustus 2025.
Sepanjang demo, setidaknya 579 orang menjadi korban kekerasan polisi dengan rincian: 334 orang ditangkap dan ditahan semenan-mena, 152 orang mengalami luka-luka akibat serangan fisik, 17 orang terpapar gas air mata, serta 65 lainnya menghadapi penahanan sekaligus kekerasan (BBC News Indonesia, 8 September 2025).
Dalam kasus Delpedro Cs, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyoroti prosedur penangkapan yang dilakukan tanpa “tertangkap tangan”, tanpa surat perintah resmi, penggeledahan tanpa izin pengadilan, bukti-bukti yang dipaparkan polisi “lemah”, dan sejumlah prosedur hukum yang dilanggar.
Untuk mempersoalkan sejumlah hal tersebut, TAUD telah mengambil langkah hukum yakni praperdilan mewakili Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru), Muzaffar Salim (Staf Lokataru), Khariq Anhar (Mahasiswa Universitas Riau), dan Syahdan Husen (Aktivis Gejayan Memanggil), bahkan sidang perdana dijadwalkan 17 Oktober 2025 mendatang.
Perlu diingat, data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa penangkapan aktivis bukan insiden tunggal — melainkan bagian dari respons struktural terhadap dinamika protes yang dipertontonkan oleh rezim ini kepada warga. Di saat bersamaan, publik mempertanyakan pidato Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa “dalang dan pendanaan aksi” di Indonesia yakni berasal dari uang koruptor, asing, dan terorisme. Jika negara gagal membuktikan sejumlah entitas yang disebut-sebut tersebut; maka bukan berlebihan jika Negara telah menyampaikan retorika kosong untuk mendapatkan kepercayaan warga.
Pola Berulang: Darimana Akar Masalahnya?
Melihat sejarah nasional, rezim otoriter maupun demokratis di Indonesia pernah menggunakan kekuatan negara untuk meredam kritik: dari “penculikan aktivis” era 1997–1998 hingga kriminalisasi pasca-Reformasi.
Kenapa pola ini terus hidup? Dalam beberapa riset menyimpulkan; karena negara atau aparaturnya melihat ruang sipil sebagai ancaman narasi—kritik dianggap lawan, bukan alat koreksi. Maka ketika protes besar muncul, maka negara seringkali melakukan penangkapan, kriminalisasi, intimidasi, dan pemidanaan yang dipaksakan kepada merak yang berkata benar.
Dalam kasus Delpedro, misalkan, sangkaan “penghasutan” (Pasal 160 KUHP) dan pelibatan pasal UU ITE, UU Perlindungan Anak menjadi piranti hukum yang fleksibel tapi rawan disalahgunakan. Langkah ini bukan kepentingan penegakan hukum, melainkan evolusi dari cara lama: kriminalisasi terhadap penyampaian pendapat dan upaya masyarakat sipil dalam memberikan bantuan hukum gratis/struktural melalui hukum pidana.
Lebih jauh lagi, laporan sejumlah organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa serangan terhadap pembela HAM dan aktivis lingkungan meningkat tajam beberapa tahun terakhir—semakin sering bersuara lantang, mengukap bisnis pejabat negara, mengkritik kebijakan yang ugal, maka akan disasar, serta berujung “ditrali besi”.
Basis Analisis: Apa yang Sesungguhnya Terjadi dalam Kasus Delpedro dan Muzaffar?
Aparat sering menggunakan jargon “keamanan publik” untuk melegitimasi operasi represif. Tapi kenyataannya, banyak massa yang ditangkap bukan pelaku kekerasan. Di Jakarta, ratusan massa ditahan— bukan karena terlibat kerusuhan, melainkan sekadar hadir di sekitar lokasi demo dan memberikan bantuan hukum gratis.
Penangkapan aktivis HAM seperti Delpedro dan Muzaffar adalah bagian dari kriminalisasi terhadap kerja-kerja advokasi dan pendampingan hukum kepada publik yang konsisten dilakukan Lokataru.
Jika ditarik mundur, penangkapan di malam hari tanpa prosedur yang jelas, tanpa pendamping hukum, penggeledahan serampangan, penyitaan barang elektronik, buku, spanduk, dan sejumlah kartu serta dokumen tanpa kejelasan tujuan, serta penetapan tersangka dengan alat bukti lemah merupakan sinyal betapa kekuasaan mengutamakan pola-pola bertentangan dengan hukum itu sendiri. Ini menciptakan efek intimidasi: publik melihat bahwa hukum bisa dibengkokkan ketika menyentuh kepentingan yang “disponsori” oleh kekuatan yang lebih besar di atasnya.
Bahkan, setiap penangkapan aktor publik — terutama yang dikenal memberikan kritik konsisten — mengandung pesan terselubung kepada masyarakat lain: “jika kamu bersuara, ini bisa jadi nasibmu.” Efek ini menghantui ruang digital dan fisik. Dan dengan makin banyak aktor sipil yang disasar, solidaritas pun bisa terkikis karena partisipasi dianggap risiko.
Selama ini, sedikit sekali aparat yang diciduk atau diadili terkait pelanggaran terhadap hak sipil. Impunitas menjalar sebagai norma, bukan pengecualian. Laporan sejumlah lembaga misalnya, banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis oleh polisi, belum ada proses pidana tuntas terhadap petugas yang terlibat. Akibatnya: aparatur tidak merasa diawasi secara serius, dan strategi represif tetap tersedia sebagai opsi mudah.
Kesimpulan dan Ancaman Nyata
Penangkapan Delpedro Cs adalah manifestasi terkini dari strategi sistemik pengkerdilan ruang sipil. Ia melukiskan sebuah negara yang semakin menyoalkan suara kritis, dan lebih memilih menegakkan “ketertiban” dengan tangkapan, bukan merespon kegelisahan masyarakat melalui dialog yang adil dan setara.
Jika praktik ini diteruskan, demokrasi Indonesia akan makin kehilangan maknanya. Kebebasan sipil akan luar biasa rapuh ketika “suara berbeda” dipaksa berpikir ulang untuk buka mulut. Negara yang pangkas ruang kritis dengan logika keamanan negara, akan melahirkan warga pasif—warga yang takut menatap tirani melalui pena ataupun megafon.
Negara ini punya alat legal untuk melindungi hak sipil: konstitusi, KUHAP, UU HAM, standar internasional. Namun bila alat itu disandera oleh kepentingan kekuasaan, maka hukum hanyalah topeng legitimasi.
Maka, saatnya publik bersuara lebih keras agar didengar oleh pembuat dan pemangku kebijakan; Mendesak Presiden Prabowo agar mengusut tuntas dalang dan pendana kerusakan Agustus 2025, Kapolri Listyo Sigit segera menyampaikan secara transparan terhadap seluruh tindakan aparat yang mengabaikan prosedur hukum; Komnas HAM segera mengambil tindakan konkrit, dan warga harus memperluas solidaritas untuk membebaskan mereka yang mendekam di rumah tahanan Polisi.
Hasnu Ibrahim adalah Manajer Penelitian dan Pengetahuan Lokataru Foundation, Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta



















